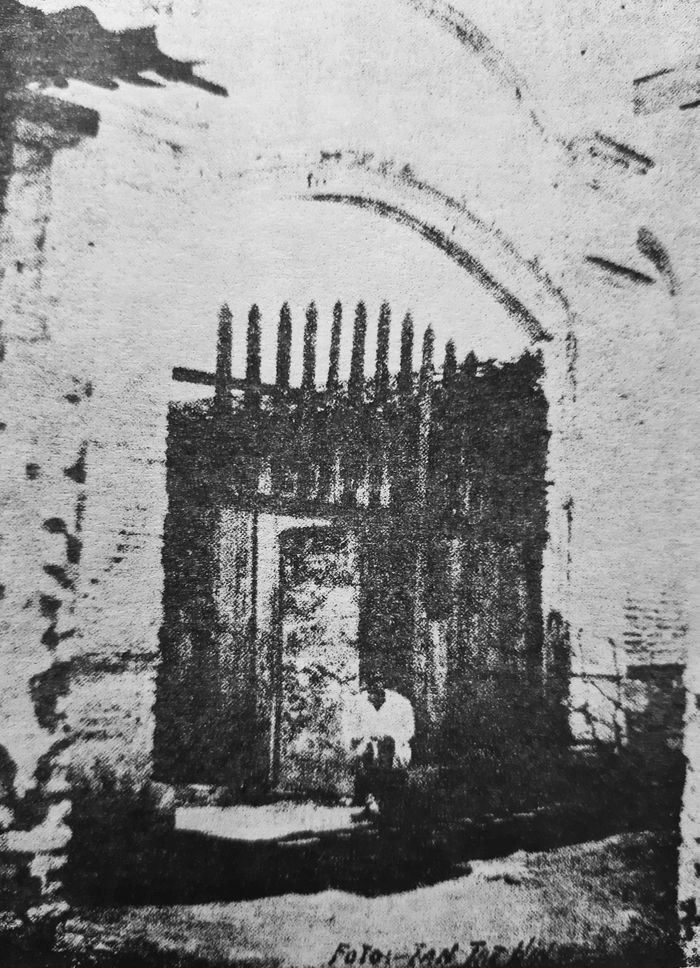
Tampaknya perbedaan keyakinan tidak menghalangi mereka untuk memberikan teladan hidup bertetangga.
Awalnya kisah tentang kehidupan sosial dan budaya orang-orang Tionghoa di Semarang diungkap Liem dalam seri catatannya yang terbit di majalah Djawa Tengah Review pada Maret 1931 hingga Juli 1933.
Selanjutnya pada paruh kedua 1933, untaian tulisan Liem dalam majalah itu disatukan dalam buku berjudul Riwajat Semarang : dari djamannja Sam Poo sampe terhapoesnja Kongkoan. Lalu, sekitar satu dekade silam buku tersebut diterbitkan ulang.
Meskipun tampaknya Pecinan Semarang selamat dari aksi penjarahan dan pembantaian, peristiwa kecamuk Perang Jawa telah menjadi suatu tengara masa bagi warga setempat. “Banyak anak-anak Tionghoa atau orang pribumi yang lahir pada zaman itu diberi nama Geger,” ungkap Liem, “untuk peringatan bahwa anak itu telah lahir saat zaman gegeran.”
Sejarah mencatat, Tan Tiang Tjhing diangkat sebagai letnan tituler pada 1809 dan menjadi mayor Cina pertama di Semarang pada 1829. Setahun sebelum menjabat sebagai mayor, jabatan kapitan diwariskan kepada putranya, Tan Hong Yan. Nama ayah dan anak ini sohor karena turut menguasai bisnis madat di Jawa pada awal abad ke-19.
Baca juga: Makam Serdadu dan Anjing Kesayangannya yang Dibantai Laskar Dipanagara
Hubungan Jawa dan Cina bagai pasang-surut air laut di negeri ini. Sebelum Perang Jawa, apakah hubungan mereka selalu dalam kebencian?
Saya menjumpai Carey lagi. Kali ini kami berbincang di kediamannya yang anggun, tepi timur Kali Cisadane, Tangerang Selatan. Di ruang tamunya, dia memajang lukisan potret Pangeran Dipanagara bergaya kontemporer.

