Susan Goldberg, Editor in Chief National Geographic, pernah mengatakan, “Kami meyakini kekuatan ilmu pengetahuan, penjelajahan, dan cara bertutur untuk mengubah dunia.”
Saya pun meyakini peran ilmu pengetahuan dalam mengubah cara pandang kita tentang kehidupan. Penemuan teknologi di setiap peradaban merupakan jawaban peradaban itu dalam meretas kesulitan. Salah satu penelitian telah menunjukkan cara pandang nenek moyang kita terhadap alam, yang mungkin dapat memberi inspirasi kepada kita tentang bagaimana seharusnya hidup berbudaya bersama alam.
Baca juga: Perubahan Iklim Menenggelamkan Kekayaan Arkeologi di Arktika
Kita menyukai penjelajahan. Sejak nenek moyang kita meninggalkan Afrika sekitar 75.000 tahun silam, dorongan untuk melintasi batas pengetahuan manusia telah membentuk kebudayaan kita. Tampaknya, kita mewarisi jiwa nenek moyang yang tak lelah mengembara. Saya beberapa kali berkesempatan mengikuti ekskavasi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Lewat penjelajahan, saya juga menyaksikan betapa para arkeolog berupaya menyingkap berbagai temuan—yang mencengangkan—tentang peradaban kita pada masa silam. Dari temuan sepetak kawasan di Trowulan yang diduga bagian dari keraton Majapahit, peradaban gua dan makna gambar cadas, hingga temuan kapal selam semasa perang dunia kedua.
Kita juga dapat mengubah pemahaman masyarakat melalui bagaimana cara bertutur. Salah satu kiatnya, kita mencoba mewartakan kepada masyarakat, dengan cara melibatkan mereka dalam tema-tema penting dan mendesak. Harapannya, masyarakat bisa lebih memahami permasalahan dan turut dalam proses pelestarian lantaran tema tersebut bagian dari kehidupan mereka.
Fenomena Belenggu Arkeokrat?
Saya mengadaptasi istilah yang digunakan Andrew Goss dalam judul bukunya Floracrats: State-Sponsored Science and the Failure of the Enlightenment in Indonesia, terbit pada awal dekade ini. Goss bercerita tentang ilmuwan-ilmuwan botani di Indonesia yang terjebak dalam kelas birokrat—yang dia juluki “Floracrats”. Kendati ilmuwan, mereka terbelenggu oleh segala aturan negara tentang apa yang seharusnya mereka teliti.
Saya melihat ada kemiripan dengan apa yang terjadi dalam dunia ilmuwan arkeologi di negeri ini. Para peneliti sebuah situs yang berpotensi memiliki temuan akbar, tampaknya harus rela untuk meneliti dalam jangka waktu yang sangat pendek. Penelitian pasti menghasilkan temuan, namun berjalan sangat pelan. Saya memahaminya, mungkin karena dana yang terbatas, atau juga penelitian itu belum menjadi prioritas negara.
Baca juga: Ketika Ahli Arkeologi Singkap Pluralisme Prasejarah Nusantara
Pemikiran ini tidak bermaksud menegaskan bahwa sebuah penelitian harus menyingkap tuntas apa yang ingin kita ketahui. Kadang, para ahli arkeologi pun harus rela menyisakan banyak pertanyaan yang kita sendiri belum mampu menjawabnya.
Sementara penelitian reguler tetap berjalan, apakah memungkinkan apabila pemerintah memberikan semacam kompetisi antarpeneliti untuk membuat proposal penelitian yang cemerlang? Kelak, proposal yang memenuhi kriteria akan menjadi proyek penelitian unggulan. Penelitian inilah yang akan mendapatkan prioritas hibah pendanaan lebih besar sehingga penelitian bisa lebih mendalam.
Ketika Profesor Riset Harry Truman Simanjuntak masih berkarya di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, saya teringat ucapannya tentang wajah arkeologi di Indonesia.
“Arkeologi berangkat dari kelampauan, bermuara pada kekinian, dan berproyeksi ke masa depan. Luar biasa bukan?” ucap Pak Truman dengan intonasi yang mantap. Kemudian, beliau buru-buru melanjutkan bicara, “Tetapi, arkeologi adalah ilmu yang sepi dari tepuk tangan, langka dalam perbincangan, dan jauh dari kemewahan atau kekayaan.”
| Penulis | : | Mahandis Yoanata Thamrin |
| Editor | : | Mahandis Yoanata Thamrin |
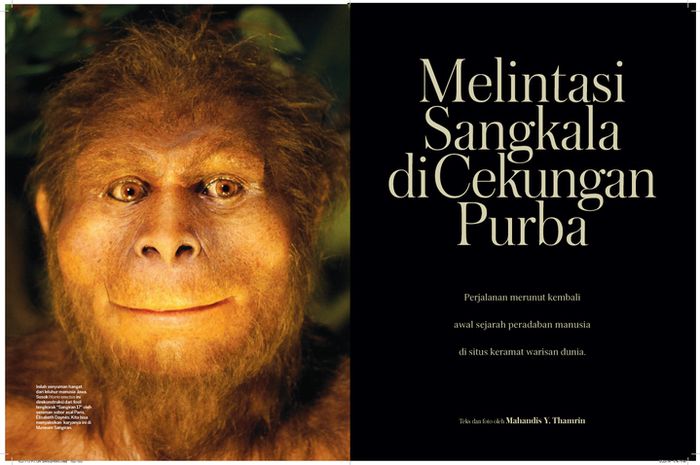



KOMENTAR